Fenomena “pelakor” adalah bukti ketimpangan jender dan minimnya kesadaran jender, bahkan di antara perempuan sendiri.
BICARA soal emansipasi perempuan di Indonesia, tentu kita tidak bisa melupakan sosok Raden Adjeng Kartini.
Semasa hidupnya, Kartini berkeinginan memajukan perempuan-perempuan Indonesia yang masih dikungkung adat. Dia melihat kebebasan perempuan-perempuan Indonesia masih tertinggal jauh dibanding perempuan Eropa.
Perempuan pada masa Kartini harus mau dipingit, dijodohkan—dan bahkan dimadu—, serta dilarang bersekolah.
Ide-idenya terus berkobar sekalipun Kartini sudah meninggal. Buku Habis Gelap, Terbitlah Terang yang berisi surat-surat Kartini menginspirasi pergerakan perempuan Indonesia.

Sekarang, sudah menjadi lazim seorang perempuan Indonesia bisa bersekolah dan bekerja.
Namun, rupanya diskriminasi terhadap perempuan masih belum hilang walau bentuknya tak lagi sama dengan yang dulu.
Fenomena “pelakor”, misalnya, adalah bukti ketimpangan jender dan minimnya kesadaran jender, bahkan di antara perempuan sendiri.
Harti Muchlas, Direktur Rifka Annisa, sebuah organisasi yang bergerak dalam perlindungan perempuan, mengatakan, bila Kartini melihat fenomena ini, dia akan merasa sedih.
“Dia (Kartini) tahu bahwa banyak perempuan belum terdidik dan sadar atas persoalan ketidakadilan yang menimpa mereka,” ujarnya kepada Kompas.com melalui pesan singkat yang diterima pada Rabu (18/4/2018).
Ketimpangan jender
Tanpa dibarengi istilah sepadan untuk laki-laki yang tidak setia, istilah “pelakor”— akronim dari “perebut (le)laki orang”—merupakan retorika timpang yang berpihak pada laki-laki.
Dalam artikelnya untuk The Conversation, Visiting Scholar di Auckland University of Technology Nelly Martin mengatakan, secara sosiolinguistik, istilah ini sebetulnya digunakan oleh masyarakat untuk menyalahkan dan mempermalukan perempuan.
"Perempuan mendapat stigma berkali-kali lipat, sementara laki-laki yang harus bertanggung jawab terhadap perilaku kekerasannya itu tidak mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat."
Sementara itu, lanjut dia, laki-laki yang melakukan perselingkuhan malah sama sekali tidak disalahkan.
Pasalnya, istilah “pelakor” menempatkan laki-laki sebagai pelaku yang tidak berdaya dan bisa direbut.
“Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menyalahkan pelakor seorang menunjukkan bias negatif kita terhadap perempuan, dan pada saat yang sama mengglorifikasi laki-laki. Dalam kasus perselingkuhan, tampaknya masyarakat Indonesia masih menerapkan bias jender,” tulis Nelly.
Harti pun berpendapat sama. Dalam wawancaranya untuk artikel Kompas.com, Kamis (8/3/2018), Harti menegaskan bahwa perselingkuhan merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya, masyarakat melupakan hal tersebut.
"Perempuan mendapat stigma berkali-kali lipat, sementara laki-laki yang harus bertanggung jawab terhadap perilaku kekerasannya itu tidak mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat," kata Harti.
Stereotip jender
Ketimpangan ini, menurut Katrin Bandel—dosen Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma sekaligus ahli dalam kajian jender—juga merupakan akibat dari stereotip jender di masyarakat.
Stereotip tersebut telah pula menyusupi media massa sehingga menyederhanakan kasus-kasus perselingkuhan. Perkara yang sejatinya merupakan relasi pribadi yang sangat kompleks menjadi berita-berita pelakor yang sensasional.
Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni mengatakan, perempuan terkonstruksikan disanjung lebih karena fisiknya atau sebagai orang yang mudah disanjung.
"Karena itu, kalau ada suami yang berpaling artinya dia beralih perhatian ke pelakor karena ada yang dibandingkan dengan istrinya, biasanya fisik," kata Budi kepada Kompas.com, Rabu (18/4/2018).
Di sisi lain, laki-laki dianggap memang sudah sewajarnya tidak memiliki kontrol diri yang kuat dan mudah tergoda.
Katrin mengatakan, ada pandangan bahwa laki-laki seakan-akan secara “alami” memang lebih mudah tergoda, bangkit hasrat seksualnya, dan bahwa salah perempuan-lah kalau perselingkuhan terjadi—karena perempuannya terlalu menggoda.
Padahal, stereotip tersebut tidak khas Indonesia, serta tidak didukung oleh ajaran agama apapun dan realitas di masyarakat.
“Justru yang agak aneh adalah, saya rasa konsep maskulinitas di Jawa umumnya tidak demikian. Laki-laki terhormat diekspektasikan sangat bisa mengontrol emosinya, termasuk syahwatnya,” ujar Katrin, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (24/2/2018).
“Dalam budaya Jawa, kesannya sangat kurang jantan kalau seorang laki-laki mengumbar emosinya," imbuh Katrin.
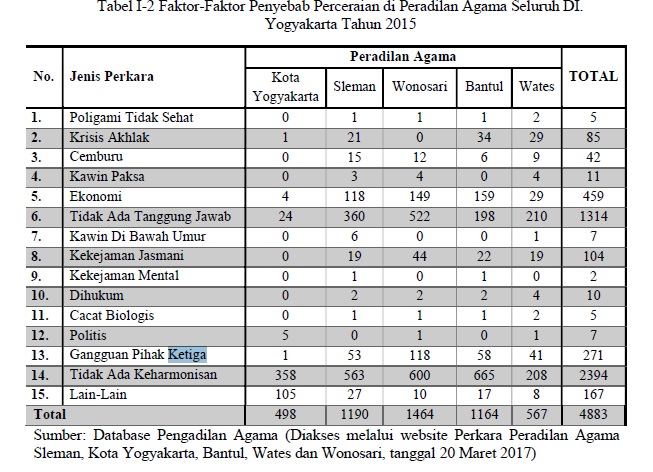
Ketidaksadaran jender
Lebih mirisnya, kaum perempuan malah kerap kedapatan turut melanggengkan ketimpangan dan stereotip jender, yaitu ketika mereka hanya menyalahkan perempuan lain dan bukan lelaki yang melakukan perselingkuhan.
Di samping faktor ketergantungan ekonomi maupun sosial yang membuat perempuan enggan meninggalkan hubungannya yang penuh kekerasan dan sekadar berharap agar kekerasan berhenti dengan sendirinya; pemahaman di kalangan perempuan sendiri yang masih sangat bias jender turut memengaruhi perilaku ini.
Perempuan mengamini peran jender tradisional sebagai makhluk nomor dua yang harus taat pada suami, dan lain sebagainya. "Itu yang sebetulnya yang menjadi akarnya," tegas Harti.
Very Handayani, aktivis teater yang sering menyuarakan isu-isu perempuan, juga sependapat. Dia mengatakan, selama ini perempuan Indonesia dididik untuk bersikap lemah lembut, sedangkan urusan berkelahi menjadi milik laki-laki.
Perbedaan ini, ujar Very, mungkin membuat perempuan (dalam hal ini istri) mencari lawan yang sebanding, yaitu sesama perempuan yang diduga atau terbukti menjadi "wanita idaman lain" (WIL) pasangannya.

Ketidakberdayaan perempuan
Seperti yang diungkapkan di atas, perselingkuhan sejatinya adalah bentuk kekerasan, baik terhadap pasangan maupun selingkuhan.
Bila perempuan sebagai istri menjadi korban karena diduakan maka perempuan di posisi pelakor dininabobokan janji-janji dan ucapan lelaki.
"Perempuan yang berdaya itu berani mengambil keputusan terhadap sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri."
“Perempuan harus punya prinsip untuk tidak mudah tersubordinat, mudah tersanjung, dan tidak berdaya, dengan sesungguhnya. Selama ini, pemberdayaan tidak dalam arti sesungguhnya, hanya semu,” kata Budi.
Berdaya yang diharapkan oleh Budi adalah berani untuk berkata tidak pada sesuatu yang tidak tepat atau tidak bermanfaat, kritis terhadap sesuatu, dan tidak mudah ikut arus.
“Perempuan yang berdaya itu berani mengambil keputusan terhadap sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Selama ini, perempuan tidak dibiasakan ambil risiko,” katanya.
Mencegah fenomena pelakor
Dalam usaha untuk memberdayakan perempuan dan mencegah fenomena-fenomena pelakor berikutnya, Harti dan Budi sependapat bahwa edukasi adalah kuncinya.
Dari lingkungan pertama, yakni keluarga, perspektif dan nilai-nilai yang tepat harus ditransferkan kepada anak oleh orangtua dengan cara membangun kedekatan dan bertukar pikiran.
Media massa dan masyarakat harus turut serta menyebarkan banyak cerita dan tulisan yang lebih seimbang dan tidak memojokkan perempuan.
Lalu, perempuan juga harus ditumbuhkan kesadaran jendernya melalui ruang-ruang konseling dan program-program pemberdayaan yang didukung oleh negara.
Lisa Oktavia, Wakil Direktur Rifka Annisa menjelaskan, dalam konseling seorang konselor psikologi akan melakukan penilaian untuk mengetahui permasalahan yang dialami korban.
Setelah itu, konselor akan memberikan gambaran bagi korban bahwa kekerasan mungkin terjadi lagi bila pasangan tidak mau ikut melakukan konseling.
Meski begitu, pada akhirnya korban sendirilah yang harus memutuskan langkah berikutnya.
“Bila kemudian perempuan ini memiliki keinginan untuk berpisah dengan laki-laki itu, kita melakukan konseling psikologi,” ujar Lisa kepada Kompas.com, Jumat (20/4/2018).
Lisa menambahkan, meski punya layanan konseling psikologi dan hukum bagi perempuan dan laki-laki, lembaganya tidak memberikan konseling hukum bagi perempuan yang menjadi WIL.
Usaha Rifka Annisa dalam memberdayakan perempuan bukan pula tanpa hambatan. Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mau melapor.
Bahkan, ada korban yang tidak menyadari bahwa dia adalah korban karena faktor pemahaman yang berbeda.
Untuk mengedukasi masyarakat dan menjangkau lebih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan, Rifka Annisa bersama pemerintah pun melakukan sosialisasi ke beberapa wilayah dan menggandeng komunitas-komunitas setempat.
Bentuknya, antara lain berupa pelatihan kepada ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelas ayah dan kelas ibu.
Sosialisasi ini juga diberikan kepada anak perempuan dan laki-laki di usia sedini mungkin melalui sekolah-sekolah, universitas, kelas remaja putri, dan kelas remaja putra, untuk mencegah kekerasan seksual.
“Jadi bagaimana kami kemudian bisa membangun perspektif dalam masyarakat bahwa untuk memutus rantai kekerasan ya harus ada intervensi,” kata Lisa.

Peran laki-laki juga harus kembali dimasukkan dalam narasi dan retorik perselingkuhan. Menurut Nelly, daripada “pelakor”, istilah “wanita idaman lain” atau WIL masih lebih tepat untuk digunakan.
Akan tetapi, lanjut Nelly, bila masyarakat bersikukuh memakai istilah “pelakor”, harus digunakan juga istilah “letise” untuk menyebut “lelaki tidak setia”. Karena, kata dia, mereka berdua berkolaborasi dalam perselingkuhan.
Terakhir, Budi berpesan kepada semua wanita yang diselingkuhi untuk tidak menegur apalagi melabrak pelakor. Teguran atau labrakan itu harus diarahkan ke suaminya.
“Karena otoritas istri itu kan ke suaminya. Dalam perselingkuhan itu, kalau salah satunya enggak mau kan enggak akan terjadi. Selama suaminya teguh, tidak akan ada perselingkuhan. Jadi jangan langsung nyalahin perempuan lain, salahin suaminya,” tegas Budi.