Mudik Lebaran itu tak sekadar berlibur ke kampung halaman. Mudik itu pulang dalam makna yang dalam. Ada banyak keajaiban bisa datang darinya. Bagaimana bisa?
MUDIK Lebaran itu pulang. Tidak sekadar pulang ke kampung halaman, meski itu lokasi yang dituju.
Ada memori dari masa lalu. Ada nilai dari tempat asal. Ada pula cerita bersama sekelompok orang yang mengenal diri kita sejak sama-sama belum disesaki embel-embel.
Seorang kawan dalam salah satu perjalanan mudik beberapa tahun silam, menyebut, "Mudik adalah menziarahi perjalanan diri sendiri hingga sampai ke titik pencapaian saat ini."
Berat ya?
Dipikir-pikir, bisa jadi memang begitu. Bukankah mudik itu misterius kalau dicermati?
Sudah tiket mahal kalau naik transportasi umum, berjejalan, banyak pengeluaran untuk oleh-oleh atau berbagi rezeki dengan kerabat di kampung, macet juga bagi yang mengendarai kendaraan pribadi. Capek, sudah tentu.

JEO ini akan mengorek ringkas asal-muasal tradisi mudik yang lekat dengan Idul Fitri di Indonesia. Namun, mudik juga tak cuma soal sejarah, kerepotan, dan hal-hal material.
Bahkan, mudik tahun ini bisa jadi punya posisi strategis. Setelah sekian waktu anak bangsa tampak "terbelah" oleh kontestasi politik praktis, mudik adalah momentum untuk menguji bersama arti kita bersaudara di Bumi Indonesia.
Lalu, karena lekat pula dengan Idul Fitri, mudik juga punya dimensi bernama "kata maaf". Seperti apakah kekuatannya bila bukan semata ucapan hapalan di bibir? Ada keajaiban menanti dari kekuatan maaf.
Dosen sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengatakan, tradisi mudik Lebaran ditengarai sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Mataram Islam.
"Awalnya, mudik tidak diketahui kapan. Tetapi ada yang menyebutkan sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam," kata Silverio, saat diwawancara Kompas.com pada 6 Mei 2018.
Kala itu, kekuasaan kerajaan Majapahit sudah sampai ke Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Oleh karena itu, pihak kerajaan Majapahit menempatkan pejabatnya ke berbagai wilayah untuk menjadi pemimpin setempat.
Para pejabat itu pun akan kembali ke pusat kerajaan untuk menghadap Raja dan melihat kampungnya. Hal itulah yang sering dikaitkan dengan mudik di Nusantara.
Silverio menambahkan, selain Majapahit, mudik juga dilakukan dari Mataram Islam yang berada di daerah kekuasaan.
"Mudik juga dilakukan oleh pejabat dari Mataram Islam yang berjaga di daerah kekuasaan. Terutama mereka balik menghadap Raja pada Idul Fitri," kata Silverio.
Namun, istilah mudik baru tren pada 1970-an. Tradisi itu dilakukan oleh perantau di berbagai daerah untuk kembali ke kampung halamannya. Terutama, mereka yang bekerja di Ibu Kota.
"Mudik menurut orang Jawa itu kan dari frasa mulih dhisik yang bisa diartikan pulang dulu. Hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah mereka menggelandang (merantau)," ujar Silverio.
Selain itu, mudik juga kerap dikaitkan dengan kata dalam bahasa Betawi, yakni "udik" yang berarti desa atau kampung. Sejarawan JJ Rizal, mengatakan, secara bahasa, mudik memang asalnya dari kata "menuju ke udik" atau kembali ke desa.
Kata mudik menjadi lekat dengan bahasa Betawi tak bisa dilepaskan dari arus urbanisasi besar-besaran ke Jakarta.
Kebijakan ekonomi pemerintah sejak awal Orde Baru yang membuat ekonomi berputar lebih cepat dengan perputaran uang berpusat di kota ini, menjadi penjelasannya.
Dosen komunikasi politik Universitas Paramadina, Eka Wenats Wuryanta, menyebut mudik sebagai tradisi balik ke sumber.
"Mengembalikan kapital sosial, bentuk dari rekonsiliasi sosial secara tidak langsung melalui adat dan budaya," ujar Eka lewat percakapan telepon, Senin (3/6/2019).
Dikaitkan dengan agama, Eka pun berkeyakinan mudik bisa menjadi salah satu sarana pereda polarisasi akibat kontestasi politik.
"Kesalehan sosial yang didengungkan selama Ramadhan dan bersimpul pada perayaan Lebaran, seharusnya bisa efektif memulihkan relasi sosial masyarakat," sebut dia.
Ibarat kata, mudik bersama seluruh rangkaian ritualnya adalah oase untuk mengembalikan rajutan keluarga dan sosial.
"Ini oase yang sebenar-benarnya oase. Diingatkan dari tahun ke tahun," kata Eka.
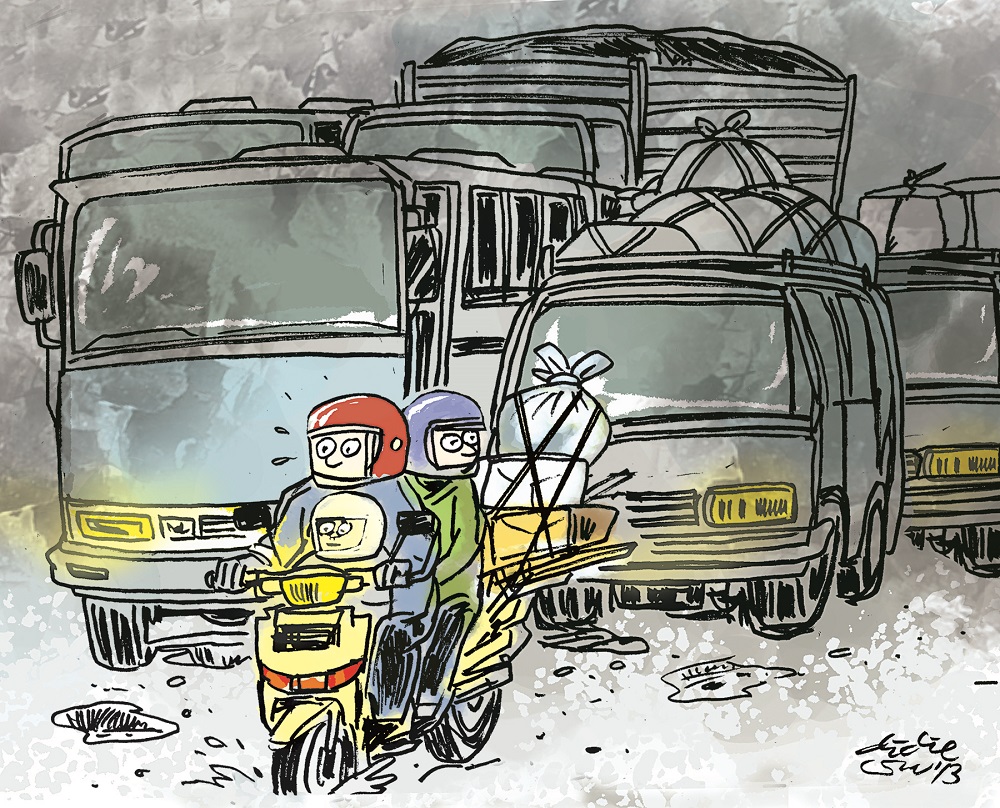
Dalam oase bernama tradisi mudik ini, lanjut Eka, nuansa permaafan juga kental, membawa setiap insan ke kondisi asali dan polos.
"(Termasuk untuk) membuka kemungkinan-kemungkinan tentang kebenaran, kejujuran, keadilan (atas relasi-relasi sosial di kenyataan). Ini yang harus terus diperjuangkan ke depan," ungkap Eka.
Tantangannya, sebut Eka, tradisi ini jangan sampai hanya berhenti pada kerepotan cara pulang kampung dan atau basa-basi permintaan maaf yang menyertai ucapan selamat merayakan hari raya.
"indonesia kalau dilihat benar-benar, selalu ada yang mengejutkan. Bahkan seusai dihantam beragam persoalan karena kontestasi politik, ada sarana atau medium seperti mudik bersama ritual-ritualnya yang berpeluang mengembalikan kedamaian," papar Eka.
Karenanya, Eka berpendapat, mudik Lebaran—terutama pada tahun ini—semestinya tak cuma kental muatan sentimental sosial.
"Bisa lebih bermakna untuk mengembalikan rekonsiliasi sosial. Dengan segala ketidakpercayaan kemarin-kemarin, ayo balik lagi. Jangan hanya berpikir kepentingan pendek, tapi pikirkan (kita semua sebagai) keluarga. Pulang."
Bahkan, Eka menganalogikan situasi polarisasi Indonesia seperti situasi rumah tangga yang sedang berhadapan dengan krisis. Pada saat seperti itu, salah satu upaya yang jamak dilakukan untuk menenangkan pikiran dan menentukan langkah ke depan adalah pulang.
"Pulang untuk membangkitkan memori. Ini juga sama. Memori kerukunan, kejujuran, kepercayaan. Pulang itu mengecapi, merasakan kembali, makna-makna yang baik dalam relasi sosial," papar Eka.
Setali tiga uang, pengajar komunikasi politik Universitas Diponegoro, Wijayanto, menyebut mudik adalah ritual tahunan yang sekaligus adalah modal sosial khas Indonesia.
Sejauh pengalamannya menempuh pendidikan master dan doktoral di luar negeri, Wijayanto mengatakan, tradisi mudik dan bermaaf-maafan untuk merayakan Idul Fitri tak dia jumpai bahkan dari koleganya dari negara-negara berpenduduk Muslim.
"Mudik itu sangat berbau antropologis, bercampur budaya kita. Ada sungkem ke orangtua dan saudara. Lalu ada tradisi ujung-ujung, sowan atau bersilaturahim ke tetangga. Itu khas sekali," ungkap Wijayanto, dalam perbincangan melalui telepon, Senin (3/6/2019).
Selain antropologis dan spiritual, lanjut dia, mudik juga kental nuansa sosiologis bahkan komunikasi politik.
"Lebaran dan mudik itu momentum yang menyentuh sampai ke alam bawah sadar individu, melampaui momentum politik lima tahunan. Saya yakin ada dampaknya untuk meredam pembelahan politik yang kemarin-kemarin terjadi," kata Wijayanto.
Terlebih lagi, tutur Wijayanto, polarisasi yang mencuat selama kontestasi politik nasional juga merengkuh ruang-ruang relasi sosial. Ini, kata dia, terkait pula dengan karakter pemilu di Indonesia yang cenderung berbeda dengan negara lain sesama pengikut sistem demokrasi.
Di negara lain, ujar Wijayanto, pelaku aktif kampanye adalah partai politik. Adapun di Indonesia, peran itu dijalankan oleh tim sukses. Cara yang ditempuh tim sukses ini, sebut dia, adalah menggarap relasi sosial mulai dari arisan, grup percakapan.
"Semua saluran untuk berinteraksi atau berelasi sosial cenderung terpolitisasi selama masa pemilu. Silaturahim pada momentum mudik ini menjadi ajang yang pas untuk saling memaafkan kembali," harap dia.

Setidaknya, Wijayanto berharap momentum mudik dan berlebaran akan menjadi cara untuk meredakan ketegangan di akar rumput. Akan lebih bagus lagi bila kalangan elite politik nasional juga melakukan rekonsiliasi menggunakan momentum ini.
Bagi Wijayanto, Indonesia juga patut mensyukuri Pemilu 2019 berdekatan waktu dengan Ramadhan dan Idul Fitri. Momentum religius ini dia yakini cukup mengurangi risiko tensi politik yang lebih besar dari pemilu yang baru saja lewat.
Meski tidak serta merta menyelesaikan semua imbas kontestasi politik, Wijayanto berpendapat bahwa mudik memang memenuhi teorema terkait modal sosial.
"Ini secara teoritik. Modal sosial itu mencakup antara lain kohesivitas, kepercayaan, keterbukaan," ujar Wijayanto.
Teori modal sosial dicetuskan Robert David Putnam pada 1941. Saat itu dia menelisik mengapa kawasan utara Italia lebih maju daripada kawasan selatan Italia. Hasilnya, dia menyebut modal sosial di kawasan utara Italia merupakan jawaban yang menjelaskan perbedaan kondisi tersebut.
"Di kita, halal bihalal itu salah satu modal sosial yang kita punya. Sarana membangun lagi kepercayaan, komunikasi, silaturahim," ujar Wijayanto.
Sebagaimana hadist nabi pula, silaturahim disebut sebagai salah satu cara yang bisa membuat awet muda, panjang umur, dan bahkan banyak rezeki.
Rasionalisasinya, jalinan modal sosial berupa interaksi akan membuka pula peluang-peluang lain termasuk ekonomi. Di sini, teori modal sosial Putnam mendapatkan tempat.
"Bangsa dengan modal sosial yang baik akan lebih tahan menghadapi krisis dan tantangan, termasuk soal persatuan bangsa. Ini karena ada mekanisme norma institusi sosial itu tadi," tutur Wijayanto.
Kata maaf mungkin memiliki dampak yang berbeda-beda bagi orang per orang, dengan intensitas memberikan maaf yang berbeda-beda pula. Meski begitu, yakinlah ada kekuatan dari kata maaf ini. Bahkan, keajaiban.
Untuk mendapatkan keajaiban itu, syaratnya tidak susah. Selama orang masih punya stok maaf dalam dirinya, baik untuk meminta maupun memberikan maaf, keajaiban itu bisa muncul lagi dan lagi.

Dalam sebuah pelatihan yang penulis ikuti, para peserta diminta memejamkan mata. Hening.
Semua orang diminta melakukan perjalanan virtual ke masa lalu. Mencari residu sakit hati, dendam kesumat, ataupun kejadian traumatis terkait hubungannya dengan sesama manusia di masa lalu.
Setelah residu sakit hati itu ketemu, setiap orang diminta memaafkan mereka yang telah menyakiti itu. Sebesar apa pun kesalahan yang telah diperbuat orang tersebut, diminta untuk rela dimaafkan.
Ibarat gim atau permainan, target perburuan perjalanan virtual itu adalah mencari luka-luka batin akibat hubungan buruk yang belum termaafkan.
Cari induknya, dan untuk menghancurkan residu itu maka tembakkanlah seratus maaf. Jika kurang, seribu, selaksa, bahkan sejuta maaf yang kita miliki.
Terasa berat dan sakit. Namun, saat residu itu rontok, jiwa seolah ringan, terbang melayang, seolah lahir menjadi manusia tanpa beban, kembali ke fitrah manusia yang memang penuh maaf.
Usai prosesi tersebut, instruktur memberi aba-aba agar peserta mengakhiri perjalanan virtualnya. Peserta lalu diminta membuka mata kembali.
Tiba-tiba….”bruk...”, terdengar teman di sebelah saya terjatuh dari duduknya. Tubuhnya lunglai, lemas, dan air mata tampak meleleh. Dia jatuh pingsan. Instruktur pun segera membangunkannya.
Beberapa saat kemudian, teman tersebut bangun. Sesenggukan dan linangan air mata seolah mengatakan semua yang terjadi. Semua peserta lain diam, tak ada yang berani bertanya apa yang sedang terjadi.
“Sakit…,” kata dia seusai meminum segelas air yang diberikan instruktur. “Kesalahan dia sebenarnya sudah saya lupakan. Tapi belum pernah benar-benar saya maafkan. Sekarang saya sudah memaafkannya. Proses memaafkannya itu yang sakit, tapi setelah itu rasanya lega,” lanjut dia beberapa saat kemudian.
Untuk alasan kasus seperti inilah, instruktur tak membolehkan peserta mencoba cara itu sendirian di rumah. Harus ada pendamping. Kedengarannya sepele, tapi dendam kesumat dan luka batin adalah “racun” atau energi negatif yang bisa menggerogoti jiwa seseorang.

Jika seseorang telah mampu memaafkan kesalahan orang lain yang dianggap sebagai kesalahan terbesar yang pernah dilakukan pada diri kita, maka kesalahan-kesalahan kecil lainnya sudah tentu mudah untuk dimaafkan.
Orang-orang yang telah memaafkan masa lalunya, mampu berdamai dengan keadaan masa lalu, lebih ringan menghadapi masa depan sesulit apa pun itu. Orang-orang yang ringan memaafkan, jiwanya lebih sehat, mudah lepas dari rongrongan sakit hati.
Kata-kata maaf, entah meminta maaf atau memberikan maaf, ternyata berkhasiat seperi terapi pada diri kita sendiri. Istilahnya, auto-healing, yang bisa menyembuhkan diri sendiri.
Luka batin masa lalu, entah karena disakiti “mantan”, disakiti musuh, dikhianati orang kepercayaan, difitnah rekan kerja atau orang terkasih, atau karena cekcok dengan keluarga, tak semestinya dibawa lari sepanjang hidup.
Luka itu harus dibasuh, dibalut, hingga akhirnya kering dan sembuh. Obat apa yang bisa membasuh dan menyembuhkan luka seperti itu? Tak ada obat kedokteran dan tak ada ahli kedokteran yang mampu menanganinya. Hanya kekuatan maaf pada diri kita masing-masing yang bisa melakukannya.
Saatnya memaafkan “The power of maaf” ini memang tiada tara. Orang-orang pemaaf cenderung memiliki kesehatan jiwa yang powerfull.
Bayangkan bila seluruh anak bangsa yang selama berbulan-bulan saling mencaci di media sosial menjalankan ini semua.
Buat apa? Untuk bersama-sama melangkah dan membangun negeri yang tak bisa disanggah sedang tertinggal dibanding "teman-teman sebaya" yang merdeka semasa seperti Korea Selatan bahkan Malaysia dan Singapura.
Mudik Lebaran dan Idul Fitri, untuk kesekian kali, dapat menjadi pilihan momentumnya. Sekalipun, permaafaan tak harus menunggu Lebaran, sejatinya.
Mudik itu pulang. Pulang menemui keluarga tercinta, pulang merawat cinta yang tak terkata-katakan, menjalin tali persaudaraan, menjumpai masa lalu, berdamai dengan keadaan, pulang membasuh luka batin, serta pulang untuk meminta maaf dan memaafkan mereka yang telah menyakiti kita.
Pada akhirnya, jika kita berlapang dada untuk meminta maaf atau memaafkan, inilah momentum pulang menjemput energi berlimpah dari kekuatan maaf. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri dan ujung-ujungnya adalah kita sebagai bangsa sekaligus umat manusia.
Biar tidak terlalu berat apalagi rumit, lagu lawas ini semoga bisa bikin senyum-senyum sendiri sembari mudik Lebaran dan merawat kekuatan maaf: